Opini
Generasi Hilang? Job Hugging dan Lonely in the Crowd
Fenomena job hugging semakin ramai diperbincangkan di media sejak tahun 2025. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika pekerja
Oleh Nivi Ardillah,S.Pd.
TRIBUN-SULBAR.COM- Generasi muda saat ini dihadapkan pada tantangan yang begitu kompleks. Meskipun lahir di era teknologi dan globalisasi, sehingga dijuluki "generasi serba bisa,& mereka pada saat yang sama dikenal sebagai generasi yang rapuh, penuh keresahan, dan kehilangan arah. Di satu sisi, dunia kerja semakin sulit ditembus, lapangan kerja terbatas, dan ancaman PHK senantiasa menghantui.
Di sisi lain, dunia sosial pun tidak lebih baik; meskipun dikelilingi jutaan koneksi digital, banyak di antara mereka yang justru merasa kesepian di tengah keramaian. Fenomena job hugging dan lonely in the crowd adalah dua potret nyata dari persoalan tersebut. Yang pertama terkait dengan dunia kerja yang makin tidak ramah bagi kaum muda, sementara yang kedua mencerminkan kehidupan sosial yang makin kehilangan makna akibat dominasi media sosial.
Keduanya lahir dari akar yang sama, yaitu sistem kapitalisme global dan sekular liberal. Sistem ini telah membangun peradaban modern yang terlihat gemerlap, namun sesungguhnya rapuh di dalam. Tulisan ini akan membongkar kedua fenomena tersebut secara mendalam, menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar pada individu, melainkan bersifat sistemik. Selanjutnya, kita akan membandingkan bagaimana Islam menawarkan solusi tuntas, bukan hanya untuk meredakan gejala, melainkan menyembuhkan penyakitnya hingga ke akarnya.
Definisi dan Realitas di Lapangan
Fenomena job hugging semakin ramai diperbincangkan di media sejak tahun 2025. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika pekerja tetap bertahan di satu pekerjaan, meskipun mereka sudah
kehilangan minat, motivasi, bahkan merasa tidak bahagia. Mereka bertahan bukan karena pekerjaan itu bermakna, melainkan semata-mata demi keamanan finansial yang esensial.
Di Indonesia, job hugging muncul seiring dengan meningkatnya angka pengangguran intelektual. Lulusan perguruan tinggi, yang awalnya memiliki harapan besar, pada akhirnya terjebak di pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang mereka. Sebagai contoh, lulusan teknik mesin mungkin bekerja sebagai staf administrasi, lulusan kedokteran justru membuka toko daring, atau sarjana komunikasi menjadi operator call center.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, survei Gallup (2024) mencatat bahwa hanya 33 persen pekerja yang merasa “engaged” atau terikat dengan pekerjaannya. Sisanya sekadar bekerja demi gaji. Banyak di antara mereka yang ingin pindah pekerjaan, tetapi tidak berani mengambil risiko karena pasar kerja yang tidak menentu.
Akar utama job hugging adalah kegagalan kapitalisme global dalam menjamin lapangan kerja yang memadai. Dalam sistem kapitalis, negara tidak lagi bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pekerjaan. Sebaliknya, tanggung jawab itu dialihkan ke sektor swasta. Perusahaan-perusahaan besar menjadi “gerbang” utama untuk mendapatkan pekerjaan, sementara negara hanya berperan sebagai regulator.
Namun, perusahaan tentu saja memiliki orientasi profit. Mereka tidak akan mempekerjakan banyak orang jika dianggap tidak efisien. Bahkan, dengan adanya otomatisasi dan kecerdasan buatan, banyak pekerjaan justru digantikan oleh mesin. Akibatnya, peluang kerja semakin sempit, sementara jumlah pencari kerja terus bertambah setiap tahun. Lebih parah lagi, kapitalisme mendorong berkembangnya praktik ekonomi non-riil dan ribawi.
Uang lebih banyak berputar di sektor spekulatif seperti saham, obligasi, dan kripto, ketimbang di sektor riil yang seharusnya bisa menyerap tenaga kerja secara luas. Industri manufaktur melemah, pertanian terpinggirkan, sementara sektor jasa berbasis digital dikuasai oleh segelintir korporasi global, memperparah ketimpangan.
Perguruan tinggi di era kapitalisme sering menjanjikan bahwa pendidikan adalah kunci masa depan yang cerah. Namun, realitas membuktikan sebaliknya. Meskipun kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri, tetap saja lulusan tidak mendapat jaminan kerja setelah menyelesaikan studinya. Sebagai ilustrasi, setiap tahun Indonesia menghasilkan lebih dari 1 juta lulusan perguruan tinggi baru. Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah ada 1 juta lowongan pekerjaan baru yang disiapkan negara untuk menampung mereka? Jawabannya, tidak. Akibatnya, persaingan semakin ketat, banyak yang menganggur, dan sebagian memilih bertahan di pekerjaan yang tidak mereka sukai karena tidak ada pilihan lain.
Dampak Psikologis dan Sosial dari Job Hugging
Fenomena ini berdampak serius karena menyebabkan pekerja kehilangan semangat kerja, mengalami stres dan burnout, tidak dapat berkembang secara profesional maupun personal, serta menurunkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, fenomena ini bisa membuat generasi muda kehilangan daya inovasi. Mereka tidak lagi berani mengambil risiko atau menciptakan hal-hal baru, karena terlalu takut kehilangan pekerjaan yang sudah ada.





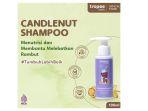














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.