Opini
Kesantunan Berbahasa Kian Meredup: Refleksi di Bulan Bahasa dan Sastra
Bahasa menjadi jembatan yang menghubungkan manusia Indonesia dalam satu kesadaran nasional.
Oleh: Nirwan Soeja
(Dosen Universitas Islam Internasional Indonesia)
TRIBUN-SULBAR.COM- Pada bulan ini, bahasa dan sastra dirayakan. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2025 bertepatan dengan peringatan hari sumpah pemuda.
Salah satu ikrar penting dalam sumpah itu adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.
Bahasa menjadi jembatan yang menghubungkan manusia Indonesia dalam satu kesadaran nasional.
Meski bahasa Indonesia mempersatukan, kenyataannya, di tingkat lokal hidup ribuan bahasa daerah dengan tata bahasa dan tata kramanya masing-masing.
Tulisan ini membicarakan kaidah tersebut yang dikaitkan dengan kesantunan dengan mengambil beberapa contoh dari salah satu bahasa di Sulawesi Barat.
Intinya adalah bahasa dan kesantunan. Di bulan bahasa ini penting untuk menengok kembali bahasa daerah kita:
Bagaimana cara kita bertutur hari ini?
Apakah masih santun atau perlahan meredup?
Istilah bahasa paralel dengan kata language dalam bahasa Inggris.
Kalau kita lihat asal usulnya, ia mengakar pada bahasa Latin, dari kata lingua yang berarti lidah—salah satu alat artikulasi dalam rongga mulut untuk menghasilkan bunyi bahasa.
Pendeknya, bahasa adalah lidah. Fungsinya adalah mewujudkan pikiran dalam bentuk konkret yang bisa didengar maupun dibaca.
Sedangkan istilah santun atau kesantunan secara umum berarti halus atau baik budi bahasanya.
Apa itu kesantunan?
Tidak ada masyarakat, khususnya dalam konteks ketimuran, yang tidak mempraktikkan nilai budaya kesantunan ini—termasuk di Sulawesi.
Konsep kesantunan berbahasa sering dikaitkan dengan istilah face atau muka. Apa itu muka? Brown and Levinson, dua ahli bahasa yang banyak meneliti tentang kesantunan menyusun pengertian konsep “muka” yang diadaptasi dari Erving Goffman.
Katanya: Ini bukan tentang wajah fisik tetapi citra diri sosial yang secara inheren ingin dilihat, dihargai dan dihormati oleh orang lain dalam komunikasi.
Sekarang kita memahami bahwa kata “muka” mengacu pada citra diri atau identitas sosial seseorang yang perlu dijaga lewat bahasa.
Konsep ini dibagi menjadi dua: muka positif dan muka negatif. Muka positif berkaitan dengan keinginan orang untuk dihargai, dihormati, dan disukai.
Misalnya, memuji, menyapa dengan hormat, memberi dukungan atau mengucapkan terima kasih.
Sedangkan muka negatif berkaitan dengan keinginan orang untuk tidak diganggu, tidak dipaksa, dan kebebasannya dihargai.
Intinya semua orang ingin diperlakukan secara santun—fitrahnya memang begitu.
Iko, Kita’
Sekarang, mari kita kaitkan dengan kata ganti iko dan kita’ dalam bahasa Pakkado’ (orang yang berbicara “saya”/dialek) yang paralel dengan kamu, engkau, anda dalam bahasa Indonesia, dan juga you dalam bahasa Inggris.
Kedua kata ini sama-sama menunjuk orang kedua tunggal tetapi memperlihatkan fungsi sosial yang berbeda. Iko dipakai untuk menyapa orang yang sebaya, lebih muda atau ada relasi keakraban.
Namun menjadi tidak santun jika ditujukan kepada orang yang lebih tua. Sebaliknya kita’—dengan tanda glottal di akhir untuk membedakannya dengan kata kita dalam bahasa Indonesia—dipakai untuk menyapa orang yang lebih tua sebagai bentuk kesantunan dan penghormatan.
Tujuannya untuk meminimalkan ancaman terhadap muka lawan bicara. Pengabaian terhadap nilai ini berpotensi menimbulkan konflik terutama jika ada perbedaan usia, status, dan posisi sosial.
Meskipun sebagian orang mungkin menganggapnya sepele, “untuk apa santun-santun? Sepenting apa dihormati? Sesungguhnya kesantunan adalah modal sosial untuk menguatkan kohesi dan menjaga budaya.
Bukan untuk terlihat baik, melainkan ini bentuk empati, perhatian dan menjadi manusia seutuhnya. Mengabaikan ini, menyebabkan kata-kata menjadi kasar, perseteruan mudah muncul, dan relasi sosial bisa retak. Inilah pendidikan bahasa yang sering kali dilupakan.
Dalam konteks menjaga identitas budaya, Iko dan kita’ bukan lagi sekadar kata, tapi soal kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan, dan soal pendidikan karakter yang diselipkan dalam bahasa.
Seseorang yang terbiasa bertutur santun cenderung lebih empati dan menghormati orang lain.
Mengabaikan kesadaran ini, kita semua kehilangan koneksi dengan warisan budaya leluhur yang mewah itu.
Sebagai contoh, coba kita lihat kemewahan bahasa daerah ini dan semua bahasa daerah di Sulawesi Barat dalam tata bahasanya secara singkat.
Ia dibangun dari struktur sintaksis yang unik, berbeda dengan bahasa Indonesia, Inggris, dan kebanyakan bahasa daerah yang ada di wilayah Barat Indonesia.
Kaidahnya unik karena subjek (pelaku kegiatan) ditempatkan setelah kata kerja, sehingga polanya seperti ini: Kata kerja + subjek, pola ini justru berlawanan dengan bahasa Indonesia, di mana subjek muncul lebih dulu, baru kata kerja.
Sebagai contoh, perhatikan kata Mandeko dan Mandeki. Mande adalah kata kerja yang berarti makan, pemarkah ko atau ki mengacu pada subjek dalam pengertian yang kultural—berkaitan dengan aspek kesantunan.
Konstruksinya sedikit mirip bahasa Latin kuno, di mana akhiran kata kerja mengalami konjugasi atau perubahan karena mengalami perubahan subjek.
Misalnya dalam kata cogito (aku berpikir), subjek terlihat melalui bunyi “o”, bila subjeknya diganti menjadi “kamu” maka bentuknya berubah menjadi cogitas, dan bila subjeknya “Dia” bentuknya menjadi cogitat.
Perbedaannya, dalam bahasa Latin, perubahan akhiran bunyi kata verba seperti contoh di atas menandakan perubahan subjek gramatikal, sedangkan dalam bahasa Pakkado’ perbedaan akhiran seperti pada kata mandeko dan mandeki menandakan perubahan fungsi sosial bahasa: dari yang kurang santun menjadi santun.
Iye’, Iyo
Kata lain yang menarik yaitu “Iye” dan “Iyo”. Kedua kata ini terlihat seperti hanya permainan bunyi, dan jika pun kita melihatnya begitu, saya kira ada benarnya. Permainan bunyi ini justru memperlihatkan kesantunan.
Secara denotatif, kedua kata itu berarti “Iya”. Iye’ adalah ekspresi yang menandakan bahwa antara penutur dan lawan bicara ada jarak sosial, ada hierarki, tapi bukan dalam pengertian untuk menindas tetapi untuk dihormati demi menjaga keseimbangan sosial. Sebaliknya, kata Iyo adalah ekspresi kesetaraan.
Secara sosial dan kultural, relasi yang terbangun bersifat egaliter, tidak ada jarak sosial dan hierarki, semuanya ditempatkan dalam posisi sosial yang sama yaitu setara.
Masih santunkah cara berbahasa kita hari ini?
Pada tahun 2022, di Awka, Nigeria, ada satu penelitian, judulnya “Penggunaan Strategi Kesantunan untuk Penyelesaian Konflik dalam Hubungan Pernikahan oleh Istri.” Responden dari penelitian ini adalah para istri (emak-emak) sebanyak 50 orang.
Hasilnya: 70 persen responden menggunakan strategi kesantunan berbahasa, sehingga suami tidak merasa harga dirinya terancam. Penelitian itu merekomendasikan agar kesantunan dalam komunikasi dipertahankan secara konsisten untuk meminimalkan konflik rumah tangga.
Bagaimana dengan keadaan kita?
Dalam berbagai debat dan talkshow, kita banyak menyaksikan pemakaian bahasa yang tidak mencerminkan kesantunan penuturnya: bahasa justru dipakai untuk menyerang pribadi dan mempermalukan sesama.
Akibatnya, diskusi menjadi kering tanpa empati dan tersesat jauh dari tujuan utamanya, yaitu mencerahkan publik.
Di media sosial atau di ruang-ruang digital, situasinya lebih serius lagi. Ujaran kebencian tumbuh subur seperti rumput liar yang tak terkendali. Kalimat-kalimat yang lahir dari amarah kerap melampaui batas kewajaran: melecehkan, menghina, dan merendahkan.
Kominfo pernah mencatat ratusan pelanggaran UU ITE setiap tahunnya terkait ujaran kebencian. Pelakunya bermacam-macam, mulai dari publik figur sampai warga biasa.
Intinya: bahasa yang seharusnya menghubungkan justru menciptakan jarak dan luka sosial. Padahal, Bolinger pernah mengingatkan bahwa “language is a loaded weapon” (bahasa adalah senjata berpeluru). Ia bisa melindungi, tetapi juga bisa melukai. Karena itu berhati-hatilah menggunakannya.
Di tingkat lokal, di wilayah yang seharusnya masih kuat nila-nilai budayanya, kini terjadi pergeseran.
Kita bisa menguji klaim ini dengan melihat keseharian di jalan, di rumah atau di sekolah: bagaimana anak-anak di kampung berbahasa kepada orang tua atau orang tua kepada anak-anak?
Apakah mereka masih mengajarkan nilai-nilai kesantunan, atau justru anak-anak belajar dari contoh yang keliru di sekitar mereka?
Keadaan itu memberitahu bahwa perubahan bahasa sejalan dengan perubahan kebudayaan.
Seperti yang pernah diingatkan oleh Edward Sapir, "Language is the most massive and inclusive art we know, a mountainous and anonymous work of unconscious generations.
"Bahasa adalah karya kebudayaan yang diwariskan lintas generasi. Jika kehalusannya terkikis, maka yang rapuh bukan hanya bahasa itu sendiri, melainkan juga peradaban yang menumbuhkannya.
Ide Sapir di atas diperkuat oleh Ludwig Wittgenstein, yang mengingatkan, “The limits of my language mean the limits of my world”—batas-batas bahasaku berarti batas-batas duniaku.
Kira-kira, ia mau bilang kalau kesantunan berbahasa memudar, maka batas dunia moral kita pun menyempit, pada akhirnya nanti kita kehilangan ruang untuk saling menghargai.
Akhirnya, saat ini, kita tidak sekadar berhadapan dengan krisis lingkungan, tetapi juga krisis etika berbahasa—krisis yang tampaknya cukup halus, namun perlahan merusak peradaban tutur kita dan merusak kesadaran moral bersama. (*)






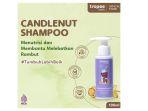














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.